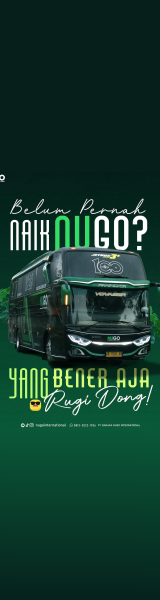Fajar di pesantren tidak datang dengan gegap gempita. Ia hadir perlahan, disambut oleh kentongan yang dipukul dengan irama khas, menandai pergantian antara malam dan pagi, antara tidur dan kesadaran. Beberapa detik kemudian, lantunan tahrim mengalun lembut, menjadi pengantar menuju adzan subuh. Suara itu merambat ke kamar-kamar santri yang sempit namun penuh kehidupan, menggugah tubuh-tubuh muda yang tertidur di atas tikar tipis. Di kamar berukuran empat kali lima yang multifungsi, tempat tidur sekaligus ruang belajar dan musyawarah kecil antarhati, tiga hingga lima santri berbagi ruang dan waktu.
Di luar kamar, di antara kabut pagi yang masih menggantung, terdengar gemericik air dari pipa yang menetes ke kolam besar di sisi belakang pondok. Dari sanalah para santri mengambil air untuk mandi dan bersuci. Air itu mengalir terus tanpa henti, dinginnya menyapa kulit dan menghidupkan rasa syukur yang sederhana: betapa kehidupan di pesantren adalah latihan untuk menerima dan merawat nikmat sekecil apa pun.
Masjid kampung berdiri berdampingan dengan pondok, tanpa sekat yang memisahkan. Di situlah denyut kehidupan pesantren berpadu dengan denyut masyarakat. Santri menjadi bagian dari warga, bukan hanya tamu. Masjid tidak sekadar tempat ibadah, melainkan ruang belajar, tempat mengaji, berdiskusi, bahkan bercermin pada kehidupan itu sendiri.
KH. Abdurrahman Wahid – Gus Dur pernah menulis “Dalam lingkungan pesantren ditekankan pembentukan nilai-nilai praktis yang diperlukan guna mengatur kehidupan sehari-hari.”
Kalimat itu bukan sekadar refleksi, melainkan potret tentang dunia yang menghidupi ajaran: bahwa belajar tidak berhenti di ruang kelas, dan guru tidak hanya mereka yang mengajar dari papan tulis. Di pesantren, pendidikan melampaui teori. Ia menjadi laku.
Di sinilah kelebihan pendidikan pesantren: tidak berhenti pada kecerdasan intelektual, tetapi meluas hingga pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kesederhanaan bukan hanya diajarkan, melainkan dipraktikkan secara terus-menerus melalui kehidupan sehari-hari. Disiplin terbangun dari jadwal harian yang ketat, tanggung jawab tumbuh dari kewajiban menjaga kebersihan, menepati giliran, dan menunaikan tugas. Kesederhanaan hadir bukan karena paksaan, tetapi karena keyakinan bahwa keberkahan hidup terletak pada keikhlasan menerima keadaan.
Pendidikan di pesantren adalah pendidikan holistik. Ia membentuk santri secara menyeluruh, tidak hanya secara intelektual tetapi juga batiniah. Santri belajar berpikir dengan kepala, bekerja dengan tangan, dan merasakan dengan hati.
Lebih dari sekadar jadwal, kehidupan di pesantren salaf menanamkan nilai-nilai fundamental yang melekat kuat pada jiwa setiap santri. Khidmah atau pengabdian, menjadi jalan utama menuju keberkahan ilmu. Santri berlomba-lomba melayani Kyai, guru, dan pesantren. Mereka meyakini, sebagaimana dawuh para ulama, bahwa ilmu tidak akan menetap di hati yang kering dari rasa hormat.
Kesederhanaan atau zuhud, terwujud dari keseharian yang serba terbatas: tidur di lantai, makan bersama dengan lauk sederhana, dan bersyukur tanpa hitung. Dari situ, lahir rasa cukup yang menguatkan batin dan menenangkan jiwa.
Kemandirian dan tanggung jawab tumbuh karena jauh dari orang tua. Santri belajar mencuci pakaiannya sendiri, mengatur waktu, dan menjaga kebersihan lingkungan secara gotong royong.
Adab dan akhlak menjadi inti dari segalanya. Hormat kepada guru, lembut kepada sesama, rendah hati dalam ilmu, semuanya diajarkan bukan lewat ceramah, melainkan melalui teladan.
Dan solidaritas komunal menjadi benang yang menenun kehidupan mereka. Dalam satu kompleks, setiap santri menjadi saudara; saling menegur, saling menolong, saling menguatkan.
Setiap detik di pesantren adalah pelajaran yang tidak tertulis di buku. Setiap tindakan, dari mencuci piring hingga membaca kitab kuning, memiliki nilai pendidikan. Di situlah pendidikan tidak berhenti sebagai sistem, melainkan menjadi cara hidup. Pesantren mengajarkan bahwa ilmu sejati bukan hanya tentang mengetahui, melainkan tentang menjadi. Menjadi manusia yang beradab, menjadi warga yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang memuliakan ilmu dan kehidupan.
Sebagaimana termaktub dalam Ta’lim al-Muta’allim,
من لم يذق ذل التعلم ساعة يبق في ذل الجهل
Man lam yadzuq dzulla at-ta’allum, sa’ah yabqa fi dzulli al-jahl.
(Barang siapa tidak pernah merasakan rendah hati dalam belajar, maka ia akan tetap berada dalam kehinaan kebodohan).
Mungkin di luar sana, dunia terus berlari mengejar pencapaian. Namun di pondok-pondok kecil itu, ada keheningan yang justru menumbuhkan sesuatu yang lebih besar: kesadaran. Bahwa ilmu sejati tidak selalu berisik, kadang ia hadir dalam diam, mengalir seperti air dari pipa ke kolam besar… jernih, tenang, dan membawa kehidupan.
Maka dari itu, setiap pagi di pesantren bukan sekadar awal hari, melainkan awal kesadaran baru. Kesadaran bahwa pendidikan sejati tidak hanya membentuk akal, tetapi juga menata hati dan mengajarkan cara hidup yang berakar pada nilai-nilai abadi.
Ahmad Taufiq
Lakpesdam PCNU Kab. Magelang