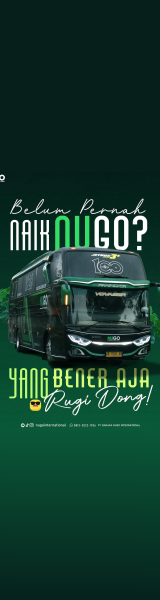Kabut pagi turun perlahan di kaki Merapi. Dari kejauhan, suara mesin diesel menggema, menembus sunyi pedesaan yang baru terbangun. Jalan desa yang sempit berguncang tiap kali rombongan truk bermuatan pasir melintas, meninggalkan debu yang mengambang di udara dan getaran yang terasa sampai ke dinding rumah. Seorang ibu di teras menutup jendela rapat-rapat, sementara anaknya menunggu giliran menyeberang jalan dengan hati-hati. Di sinilah, di tepian Gunung Merapi yang gagah dan penuh berkah, kesunyian alam telah lama terkalahkan oleh dentum mesin dan derak roda baja.
Aktivitas penambangan pasir sudah bertahun-tahun menjadi denyut kehidupan baru di wilayah Kabupaten Magelang bagian timur dan tenggara. Penambangan tersebar di lima kecamatan: Dukun, Srumbung, Salam, Muntilan, dan Ngluwar. Wilayah yang dulunya menjadi sabuk hijau penyangga Merapi kini seolah tak pernah tidur. Dari aliran Kali Putih, Kali Pabelan, hingga Kali Senowo, truk-truk pengangkut pasir datang silih berganti, menjemput hasil bumi yang tak pernah selesai digali.
Ciri khas jalan raya Magelang–Semarang kini bukan lagi pemandangan sawah atau kebun salak, melainkan deretan truk pasir yang melata dengan muatan berlebih. Beberapa mogok di tanjakan atau bahu jalan karena as patah atau ban meletus akibat beban berat. Di warung “Ngetemp” di tepi jalan, para sopir menunggu giliran, mengistirahatkan ban yang panas karena gesekan aspal. Mereka bercanda ringan tentang “TPR resmi” dan “TPR nonresmi” pungli yang wajib dibayar di pos jalan dan lokasi tambang. Tak ada yang tahu pasti uang itu mengalir ke mana: mungkin ke kantong petugas, mungkin ke pejabat rendahan yang merasa punya hak atas setiap butir pasir Merapi. Di bak belakang beberapa truk, tampak tulisan pilok putih yang menggelitik: “Kuat Lakoni, ra kuat tinggal Ngopi.” Kalimat sederhana itu terdengar seperti sindiran pahit terhadap sistem yang memaksa rakyat kecil menanggung beban permainan besar yang tak terlihat.
Penambangan pasir ilegal ini bukan fenomena baru. Aktivitasnya telah berlangsung lebih dari tiga tahun, bahkan kemungkinan jauh lebih lama dari yang diketahui banyak orang. Ia tumbuh di bawah radar pengawasan, terlindung oleh kabut birokrasi dan kepentingan ekonomi yang saling bertaut. Setelah kewenangan pengelolaan tambang ditarik dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi pada 2014 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, muncul kekosongan kontrol di tingkat lokal. Celah inilah yang dimanfaatkan jaringan penambang dan cukong pasir untuk memperluas operasi tanpa izin. Kabupaten kehilangan kuasa mengatur, tetapi tetap menanggung kerusakan yang ditimbulkan. Sementara itu, koordinasi lintas lembaga di tingkat provinsi berjalan lamban, seperti rantai berkarat yang sulit digerakkan.
Dari catatan kepolisian dan pemerintah daerah, sedikitnya ada 36 titik tambang pasir ilegal tersebar di lima kecamatan. Titik-titik galian itu muncul di sepanjang aliran sungai bekas lahar dingin, jalur yang dulu menjadi tempat air menghidupi sawah dan kebun warga. Kini, jalur itu berubah menjadi nadi ekonomi gelap yang tak kenal aturan. Di lapangan, kerusakan paling parah tampak di ruas Srumbung–Sudimoro. Warga sudah berulang kali melapor dan meminta agar jalur truk dialihkan, namun laporan itu seperti terhempas di udara.
Di sisi lain, nilai transaksi tambang pasir ilegal di lereng Merapi mencapai Rp3 triliun per tahun, sebuah angka yang menohok karena melampaui APBD Kabupaten Magelang yang hanya sekitar Rp2,76 triliun, di mana lebih dari 70 persen masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ironinya, di wilayah yang tanahnya digali dan jalannya hancur, ekonomi yang bergerak justru ekonomi hitam yang tak tercatat, sementara keuangan daerah tetap bergantung pada belas kasihan pusat.
Namun tak sepeser pun dari perputaran uang besar itu menetes ke kas daerah. Pendapatan asli daerah tidak bertambah, tetapi biaya perbaikan jalan dan infrastruktur meningkat setiap tahun. Warga sekitar hanya menjadi penonton yang setiap hari menelan debu, mendengar dentuman mesin, dan melihat sawah mereka perlahan mengering. Sementara aparat daerah terjebak dalam dilema antara menjaga ketenangan atau menghadapi jejaring kuasa yang membekingi operasi ilegal itu. Pertanyaan yang muncul: apakah mereka tidak tahu, atau justru memilih untuk tidak tahu?
Kerusakan ekologis yang ditimbulkan pun sangat serius. Sekitar 312 hektar lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang seharusnya dilindungi telah rusak akibat aktivitas tambang liar. Ekosistem hutan terganggu, habitat alami lenyap, dan bentang alam berubah drastis. Penambangan tanpa reklamasi memicu erosi, meningkatkan risiko longsor, dan mengancam ketersediaan air bersih. Di dusun-dusun seperti Salam, Ngargomulyo, dan Sudimoro, debit air menurun drastis. Sumur yang dulu tak pernah kering kini harus dipompa dalam. Irigasi sawah tersendat, pola tanam berubah, dan tanah subur berganti menjadi hamparan batu serta debu. Burung-burung yang dulu bersarang di tepi sungai menghilang tanpa jejak.
Kerusakan ekologis ini diikuti oleh retaknya tatanan sosial. Desa yang dulu guyub kini terbelah antara mereka yang menolak tambang dan mereka yang menggantungkan hidup darinya. Aparat desa terjebak dalam dilema moral: menjaga harmoni sosial atau menutup mata demi stabilitas ekonomi. Beberapa tokoh masyarakat yang berani bersuara justru diintimidasi, dicap “anti-investasi”, bahkan ada yang diperiksa karena dianggap memprovokasi. Di Srumbung dan Salam, kelompok buruh tambang seperti “buruh seng grong” pernah melakukan protes terhadap penindasan para cukong dan oknum aparat, namun suara mereka cepat dibungkam.
Perlawanan juga datang dari MWCNU bersama seluruh Jam’iyyah-nya dari Pengurus Ranting dan Badan Otonom hingga 17 kepala desa yang menuntut penutupan tambang ilegal dan pemulihan fungsi lahan. Namun perjuangan itu tidak mudah. Di tengah tekanan kekuasaan, suara moral sering kali menjadi yang paling lemah. Padahal, yang mereka perjuangkan hanyalah hak untuk hidup di tanah yang tidak rusak dan air yang tidak kering.
Tambang pasir ilegal di lereng Merapi bukan sekadar soal ekonomi hitam. Ia adalah cermin dari negara yang abai, aparat yang menutup mata, dan masyarakat yang akhirnya belajar diam. Siklusnya selalu sama: tambang dibuka, alam rusak, operasi digelar, pelaku ditangkap sebagian, lalu jaringan tumbuh kembali, seolah tak ada yang benar-benar ingin menutupnya.
Jika Merapi suatu saat kembali bergemuruh, barangkali itu bukan semata gejala geologi. Bisa jadi itu adalah bentuk protes dari gunung yang tubuhnya dikoyak tanpa ampun. Sebab alam punya cara sendiri untuk menagih utang manusia. Dan ketika tagihan itu datang, tak ada alat berat yang bisa menggali jalan keluar.
Pada akhirnya, persoalan tambang pasir di Merapi bukan hanya soal hukum, melainkan juga soal nurani dan arah kekuasaan. Pemerintah pusat selama ini tampak abai dan tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap gurita tambang ilegal yang telah merusak lereng Merapi. Lereng yang seharusnya menjadi sabuk hijau penyangga kehidupan justru dibiarkan menjadi halaman belakang kekuasaan, tempat sumber daya diambil tanpa batas sementara kerusakannya ditanggung oleh rakyat kecil. Pemerintah daerah pun tampak tak berdaya menghadapi jejaring kuasa yang membekingi operasi ilegal itu. Ketika aparat di bawah terperangkap dalam struktur yang timpang, kebenaran pun kehilangan jalannya.
Di antara debu tambang yang beterbangan dan jalanan yang retak, rakyat kecil tetap bertahan. Mereka menutup jendela agar anak-anaknya tak sesak, memompa air dari sumur yang kian kering, dan berdoa agar lahan dan sawahnya tak ikut terterjang banjir lahar dingin dari Merapi. Alam telah berteriak, tetapi kekuasaan memilih tuli.
Dan mungkin, ketika Merapi suatu hari kembali bergemuruh, itu bukan sekadar gejala geologi. Ia bisa jadi bahasa terakhir dari gunung yang tubuhnya dikoyak tanpa ampun, sebuah pengingat keras bahwa alam punya cara sendiri menagih utang manusia. Jika hari itu tiba, tak ada kekuasaan, izin tambang, atau alat berat apa pun yang mampu menggali jalan keluar.
Pertanyaan yang tersisa sederhana namun menampar:
Apakah kekuasaan hanya akan turun tangan ketika bencana sudah datang, ataukah kita memang sedang menunggu Merapi berbicara dengan caranya sendiri?
Ahmad Taufiq
Anggota Lakpesdam PCNU Kab. Magelang